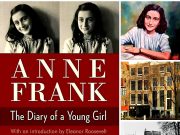Jakarta — Indonesia memiliki sejarah panjang tragedi kemanusiaan yang bersifat politis dan hingga kini belum diselesaikan secara adil. Deretan pelanggaran hak asasi manusia berat—mulai dari Peristiwa 30 September 1965 dan pembantaian massal pasca-1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997–1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, Kerusuhan Mei 1998, hingga kekerasan negara di Aceh dan Papua—menjadi luka sejarah yang terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa.
Demikian disampaikan Pengajar Filsafat di Universitas Pelita Harapan, Alexander Aur dalam Kuliah Terbuka bertajuk “Etika Memori dan Impunitas Sejarah” pada Senin, 10 November 2025, di Gedung Tempo Media Group, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Klik: Rakyat yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara dan Suara Ibu Indonesia.
Dalam pemaparannya, Alex, begitu pria ini biasa disapa menegaskan bahwa persoalan tragedi kemanusiaan di Indonesia tidak berhenti pada peristiwa masa lalu, melainkan terus berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan demokrasi hari ini. Menurutnya, kegagalan negara menyelesaikan pelanggaran HAM secara adil telah melahirkan praktik impunitas sejarah—situasi ketika kejahatan masa lalu tidak hanya luput dari pertanggungjawaban hukum, tetapi juga dinormalisasi dalam kesadaran publik.
Luka Kemanusiaan dan Memoria Passionis
Alex menjelaskan bahwa tragedi-tragedi kemanusiaan tersebut meninggalkan memoria passionis, yakni ingatan kolektif tentang penderitaan akibat kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Ingatan ini tidak hanya hidup dalam keluarga korban, tetapi juga menjadi bagian dari memori bersama rakyat Indonesia.
“Tragedi kemanusiaan bukan peristiwa biasa. Ia memuat jejak kekerasan, pengingkaran martabat manusia, dan kegagalan negara melindungi warganya,” ujar Alexander di hadapan peserta kuliah terbuka.
Namun, ingatan atas penderitaan korban, lanjutnya, kerap dikaburkan atau dihapus secara sistematis melalui kebijakan politik, narasi sejarah resmi, serta legitimasi simbolik terhadap pelaku pelanggaran HAM. Praktik semacam inilah yang disebut sebagai impunitas sejarah.
Menurut Alex, impunitas sejarah tidak bekerja secara kebetulan, melainkan dibangun melalui infrastruktur yang bersifat politik, institusional, dan afektif. Infrastruktur ini mencakup pembungkaman suara korban, stigma sosial, manipulasi ingatan kolektif, hingga argumentasi pembangunan yang dijadikan pembenaran moral atas kejahatan masa lalu.
Ia menyinggung polemik penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh dengan rekam jejak pelanggaran HAM sebagai contoh nyata bagaimana negara memproduksi impunitas sejarah. “Dalih keberhasilan pembangunan sering dipakai untuk mengaburkan fakta pelanggaran HAM dan penderitaan korban,” tegasnya.
Etika Memori: Mengingat sebagai Tanggung Jawab Moral
Alex juga menguraikan gagasan etika memori, yakni pendekatan filosofis yang menempatkan mengingat sebagai tindakan moral dan politis. Mengacu pada pemikiran Jasna Ćurković Nimac dan Paul Ricœur, ia menjelaskan bahwa mengingat bukan sekadar aktivitas psikologis, melainkan praktik etis yang membentuk relasi sosial dan arah kehidupan bersama.
“Mengingat memengaruhi cara kita menilai keadilan dan menentukan sikap terhadap sesama. Karena itu, memori harus ditata secara etis agar tidak menjadi alat kekerasan baru,” ujarnya.
Alexander memaparkan tiga prinsip utama dalam etika memori: kebenaran, keteladanan, dan kebaikan bersama. Prinsip kebenaran menuntut kejujuran terhadap fakta sejarah dan penderitaan korban. Prinsip keteladanan mendorong agar ingatan atas tragedi kemanusiaan menjadi pelajaran moral universal, bukan alat pembenaran dendam. Sementara prinsip kebaikan bersama menekankan pentingnya keseimbangan antara pengungkapan kebenaran dan upaya rekonsiliasi demi kehidupan sosial yang adil.
Alex juga menekankan pentingnya memori kolektif sebagai fondasi kohesi sosial. Mengacu pada Paul Ricœur, ia menyebut bahwa masyarakat memiliki “utang etis” kepada para korban tragedi kemanusiaan. Mengabaikan memori kolektif berarti mengingkari keadilan simbolik terhadap mereka yang telah menderita dan kehilangan suara.
“Memori kolektif bukan sekadar nostalgia atau ritual peringatan. Ia adalah ruang simbolik tempat masyarakat meneguhkan tanggung jawab terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan,” katanya.
Melalui narasi, diskursus publik, dan peringatan bersama, ingatan pribadi dapat diolah menjadi kesadaran sosial yang mencegah pengulangan kekerasan dan penindasan.
Kritik terhadap Logika Keberhasilan Pembangunan
Dalam konteks politik kontemporer, Alex mengkritik keras logika keberhasilan pembangunan yang kerap dijadikan alasan untuk mengesampingkan persoalan pelanggaran HAM. Menurutnya, baik dari perspektif etika deontologis Kant maupun utilitarianisme Bentham, keberhasilan material tidak dapat menghapus kesalahan moral jika dicapai dengan mengorbankan martabat manusia.
“Politik pembangunan yang memperlakukan manusia sebagai alat demi tujuan negara adalah politik yang gagal secara etis,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta yang menyoroti peran media, pendidikan, dan masyarakat sipil dalam merawat ingatan kolektif. Alex menilai ruang publik seperti Kuliah Terbuka Klik: Rakyat penting untuk mencegah pelupaan sistematis atas tragedi kemanusiaan.
Menutup pemaparannya, Alex menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keberanian publik menghadapi masa lalu secara jujur dan beretika. “Bangsa ini hanya bisa sembuh jika berani mengingat secara benar—bukan untuk membalas, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memulihkan martabat kemanusiaan,” pungkasnya.
Kuliah Terbuka “Etika Memori dan Impunitas Sejarah” menegaskan bahwa persoalan ingatan dan sejarah bukan sekadar wacana akademik, melainkan medan perjuangan etis dan politik yang menentukan arah kehidupan bersama. Di tengah berbagai upaya pelupaan, forum ini mengingatkan bahwa mengingat adalah bagian dari tanggung jawab kewargaan dan prasyarat bagi masa depan Indonesia yang adil dan berkeadaban.