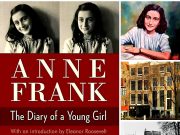Romo Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno, SJ, adalah salah satu dari sedikit imam dan filsuf Indonesia yang mampu berbicara tentang iman, seni, dan kebudayaan tanpa nada menggurui—tenang, reflektif, dan mengendap lama di benak pendengarnya.
Romo Mudji lahir di Surakarta, 12 Agustus 1954, dalam lanskap budaya Jawa yang akrab dengan simbol, laku batin, dan keheningan. Dari kota inilah kepekaan estetik dan spiritualnya bertumbuh. Masa mudanya dijalani dekat dengan Gereja, hingga akhirnya ia memilih bergabung dengan Serikat Yesus (SJ)—tarekat yang menempatkan pencarian intelektual dan keterlibatan sosial sebagai bagian dari iman.
Pendidikan filsafat dan teologi membawanya jauh dari tanah air. Di Roma, ia menempuh studi doktoral di Universitas Kepausan Gregoriana dan meraih gelar doktor filsafat. Di kota yang sarat sejarah dan pemikiran itu, Romo Mudji tidak hanya bergulat dengan teks-teks besar filsafat Barat, tetapi juga memperdalam ketertarikannya pada seni, estetika, dan pengalaman manusia konkret. Kelak, cara pandang inilah yang menjadi ciri khas seluruh pemikirannya.
Sekembali ke Indonesia, Romo Mudji menjalani hidup sebagai pendidik dan pemikir publik. Ia mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama STF Driyarkara Jakarta, tempat ia dikenal sebagai dosen (filsafat budaya dan estetika) yang mengajak mahasiswa berpikir pelan dan mendalam. Baginya, filsafat bukan sekadar teori, melainkan latihan batin untuk membaca realitas dengan jujur dan berbelas kasih.
Dari ruang kelas, gagasannya mengalir ke dalam buku dan esai. Ia menulis tentang estetika, kebudayaan, pendidikan, demokrasi, dan kemanusiaan. Karya-karyanya—seperti Estetika: Filsafat Keindahan, Getar-getar Peradaban, dan refleksinya tentang Driyarkara—menempatkannya sebagai salah satu suara penting dalam humanisme Indonesia. Sebagian tulisan akademiknya juga tercatat dalam Google Scholar, menandai kontribusinya dalam dunia ilmiah.
Namun Romo Mudji tidak berhenti pada kata-kata konseptual. Ia menulis puisi, membuat sketsa, dan berpameran. Bagi dirinya, seni adalah cara lain untuk berfilsafat—bahasa sunyi ketika konsep tak lagi cukup. Dalam garis-garis sketsanya, tampak permenungan tentang ruang, waktu, dan manusia; dalam puisinya, kegelisahan sekaligus harapan.
Keterlibatannya dalam Borobudur Writers & Cultural Festival memperlihatkan wajah lain Romo Mudji: seorang budayawan yang percaya pada dialog. Ia terlibat sebagai penggagas dan pemimpin kegiatan, menafsirkan Borobudur bukan hanya sebagai monumen sejarah, tetapi sebagai teks hidup tentang pencarian makna dan kebijaksanaan lintas iman.
Ia juga pernah memasuki ranah publik secara lebih formal, ketika dipercaya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal era Reformasi. Namun dunia administrasi negara bukanlah panggilannya yang terdalam. Tak lama kemudian, ia memilih kembali ke dunia pendidikan dan kebudayaan—ruang yang memberinya kebebasan untuk tetap kritis tanpa kehilangan keheningan.
Romo Mudji dikenal berani bersuara tentang demokrasi, pluralisme, dan toleransi, tetapi selalu dengan nada reflektif. Ia tidak menyulut kemarahan, melainkan mengajak orang berhenti sejenak dan berpikir. Di tengah zaman yang gaduh, ia memilih berbicara pelan.
Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia tetap menulis. Buku puisi Semai Kata menjadi penanda bahwa hingga akhir, Romo Mudji setia pada pencarian makna. Kata-katanya kian ringkas, tetapi justru semakin jernih.
Romo Mudji Sutrisno, SJ, berpulang pada 28 Desember 2025 di Jakarta. Ia meninggalkan dunia tanpa hingar-bingar, seperti cara ia hidup: sederhana, reflektif, dan setia pada keheningan. Warisannya bukan hanya buku dan karya seni, melainkan cara berpikir dan cara memandang manusia—sebuah undangan untuk tetap waras dan manusiawi di tengah zaman yang sering kehilangan arah.