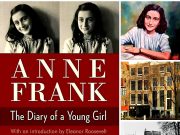JAKARTA — Lebih dari 120 juta orang di dunia saat ini hidup dalam situasi pemindahan paksa akibat perang, kekerasan, dan persekusi. Di tengah angka yang terus meningkat itu, pertanyaan mendasar mengemuka: apakah perlindungan bagi pengungsi adalah hak yang melekat pada martabat manusia, atau sesuatu yang harus “dibuktikan” melalui integrasi?
Pertanyaan tersebut mengemuka dalam Forum Praksis seri ke-17 yang diselenggarakan Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit (PRAKSIS), Jumat (13/2/2026) di Jakarta. Mengusung tema “Pengungsi dan Integrasinya ke dalam Masyarakat Lokal”, forum ini menghadirkan Rose Campion, peneliti masalah pengungsi dan mahasiswa doktoral di Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, Inggris.
Dalam paparannya, Campion menegaskan bahwa integrasi kerap dipahami secara teknis sebagai “menjadi bagian dari masyarakat”. Indikatornya meliputi status hukum, penguasaan bahasa lokal, pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, perumahan, partisipasi sosial, kehidupan keluarga, hingga rasa memiliki.
Namun, menurut dia, integrasi bukan konsep yang netral. “Siapa yang menentukan apa itu ‘integrasi yang baik’? Apakah integrasi sekadar kontribusi ekonomi? Adaptasi budaya? Atau justru menyangkut martabat dan hak asasi manusia?” ujarnya.
Jerman: Integrasi dari Atas
Campion membandingkan dua konteks berbeda, yakni Jerman dan Indonesia. Sejak tahun 2000, Jerman menerapkan kebijakan integrasi resmi yang terstruktur. Program tersebut mencakup kursus bahasa dan integrasi tanpa biaya, serta akses terhadap pekerjaan yang dikaitkan dengan kemandirian ekonomi dan peluang kewarganegaraan.
Meski kursus bahasa diberikan gratis, pengungsi yang tidak mengikuti atau gagal dalam ujian secara berulang dapat kehilangan manfaat tertentu, termasuk dukungan finansial.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa 64 persen pengungsi yang datang pada 2015 kini telah bekerja. Namun, ketimpangan masih tampak jelas: 76 persen laki-laki bekerja, dibandingkan hanya 35 persen perempuan. Selain itu, rasisme struktural dinilai masih memengaruhi akses dan proporsionalitas kesempatan kerja.
Model ini, menurut Campion, dapat disebut sebagai “integrasi dari atas”—sebuah sistem yang kuat dan formal, tetapi mensyaratkan kepemilikan dan perlindungan yang bersifat kondisional.
Indonesia: Integrasi dari Bawah
Berbeda dengan Jerman, Indonesia menampung sekitar 12.000 pengungsi, mayoritas berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Irak, dan Iran. Namun Indonesia tidak memiliki sistem suaka nasional maupun kebijakan integrasi jangka panjang.
Akibatnya, pengungsi hidup dalam ketidakpastian hukum. Mereka tidak dapat bekerja secara legal, tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi, serta terbatas dalam layanan kesehatan dan perbankan. Sebagian bahkan menunggu lebih dari 10 tahun untuk penempatan kembali (resettlement) ke negara ketiga, sementara peluang tersebut terus menurun.
Ketiadaan sistem formal ini berdampak pada tingginya tekanan psikologis dan ketergantungan pada bantuan internasional atau keluarga di luar negeri. Meski demikian, integrasi tetap terjadi.
Pengungsi membangun komunitasnya sendiri melalui Refugee-Led Organizations (RLOs). Organisasi ini menyediakan pendidikan, dukungan kesehatan mental, membantu pendatang baru, serta membangun koneksi dengan masyarakat lokal. Partisipasi sosial dan ekonomi juga terwujud melalui interaksi sehari-hari—berbelanja di pasar lokal, berolahraga bersama, hingga inisiatif pendidikan komunitas.
Situasi ini oleh Campion disebut sebagai “integrasi dari bawah” atau “belonging yang tertunda”—rasa memiliki yang tumbuh dalam keterbatasan, tanpa pengakuan formal dari negara.
Martabat sebagai Inti
Menutup paparannya, Campion menekankan bahwa kebijakan integrasi tidak semestinya berhenti pada pemberian peluang ekonomi atau administratif.
“Entah integrasi dari atas atau dari bawah, kebijakan integrasi seharusnya tidak hanya memberi peluang, tetapi juga mengangkat martabat manusia,” ujarnya.
Perbandingan Jerman dan Indonesia menunjukkan dua wajah berbeda dari integrasi: satu dengan sistem kuat namun bersyarat, yang lain tanpa sistem formal tetapi ditopang solidaritas komunitas. Di antara keduanya, pertanyaan etis tetap sama—apakah perlindungan adalah sesuatu yang harus diraih, atau sesuatu yang memang menjadi hak setiap manusia.
Forum Praksis kali ini menegaskan bahwa kebijakan publik tentang pengungsi bukan sekadar soal tata kelola, melainkan tentang bagaimana sebuah masyarakat memaknai kemanusiaan itu sendiri.