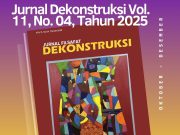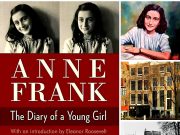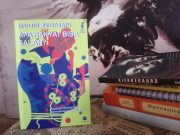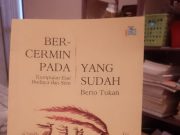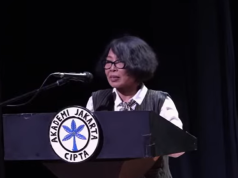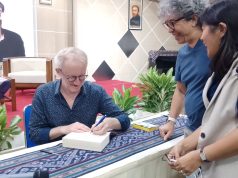Usianya kini lebih dari sembilan puluh tiga tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Bisri telah melihat tiga bendera berkibar di tanah air: Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia. Ia menyaksikan langsung bagaimana hidup berubah di bawah tiap bendera, dan bagaimana nasib manusia bisa berputar begitu cepat.
Awal Kehidupan dan Peristiwa 30 September
Oktober 1965, Bisri masih muda. Ia tinggal di sebuah desa, membantu para petani menanam singkong, talas, dan padi. Ia mengajar anak-anak muda cara bertani yang lebih baik—tanpa upah, tanpa pamrih. Saat itu, Indonesia sedang giat membangun untuk menyelesaikan amanat Revolusi 1945. Tak seorang pun menyangka bahwa di Jakarta sedang bergolak peristiwa besar yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September.
“Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Jakarta,” kenangnya. “Kami tidak punya radio, tidak ada berita apa-apa. Kami hanya petani.”
Namun beberapa hari kemudian, hidupnya berubah drastis.
Penangkapan dan Pemeriksaan
Tanggal 5 Oktober 1965, Bisri dan seorang teman berjalan ke alun-alun Pandeglang untuk menghadiri peringatan Hari ABRI. Di tengah jalan, mereka dicegat aparat.
“Mau ke mana?” tanya tentara.
“Ke alun-alun, mau lihat peringatan Hari ABRI,” jawab Bisri.
“Tidak bisa! Naik mobil!”
Tanpa penjelasan, mereka dibawa ke kantor polisi Pandeglang, lalu diserahkan ke Kodim. Malam itu mereka tidur berdesakan di lantai. Keesokan harinya, setelah apel besar, sebagian tahanan digiring ke penjara—termasuk Bisri.
Ruangan penjara sesak, makanan sangat kurang. Suatu malam ia dipanggil ke ruang pemeriksaan Kodim. Empat tentara dan seorang letnan muda bernama Mukhlas menginterogasinya dengan kasar.
“Kamu tahu peristiwa 30 September?”
“Tidak.”
“Di mana kamu waktu itu?”
“Di rumah mertua saya, di desa.”
“Bohong! Kamu orang PKI!”
Bisri menolak tuduhan itu. Karena dianggap membantah, ia dipukuli. Muka, lengan, dada, kepala tak berbentuk akibat bogem mentah yang bersarang berkali-kali di tubuhnya. Bahkan besi stebal dua jari pun dihantamkan ke tubuhnya tanpa ampun oleh para tentara. Siksaan tiada henti menghampiri tubuhnya hingga luka-luka, lebam, bengkak, berdarah. Namun Bisri bertahan.
“Saya jatuh, tapi tidak mau mengaku,” katanya. Rupanya tentara pun nyaris putus asa. Bisri pun mengatakan, “Sudah tulis saja apa yang ingin kalian tulis.”ujar Bisri. Dan kertas pengakuan itu diserahkan kembali ke Bisri setelah ditulis oleh para tentara yang menyebutkan bahwa dirinya adalah PKI, pemberontak, dan segala macam yang buruk mengenai dirinya.
Bisri diminta tanda tangan. Namun, sebelum tanda tangan, di bawah pernyataan pengakuan yang tidak pernah dilakukannya (yang ditulis para tentara itu), Bisri menulis: “Tulisan ini bukan saya yang menulis. Saya tidak tahu apa-apa, apalagi melakukan semua ini.”
Beberapa bulan kemudian, petugas lain membaca catatan itu dan sadar tulisan tersebut bukan tulisan Bisri. Sayang, kesadaran itu tidak otomatis menghapus penderitaannya.
Kerja Paksa di Pelabuhan dan Jalan Raya
Bisri mendekam tiga tahun di penjara. Banyak tahanan meninggal karena lapar dan sakit. Suatu hari, sekitar dua ratus orang tahanan sehat dipilih dan dinaikkan ke truk. Mereka dibawa menuju pantai, ke Pelabuhan Karangantu di Banten. Di sanalah mereka diperintahkan membangun kembali pelabuhan yang rusak—dengan cangkul, sekop, dan palu bambu.
“Tanahnya liat, berlumpur. Kami menggali sedalam tujuh meter, dan lebar lima meter,” katanya. Mereka bekerja dari pukul enam pagi sampai tengah malam, tidur hanya tiga jam sehari. Setelah setahun, pelabuhan itu selesai. Tapi mereka tidak bebas. Perintah baru datang: membangun jalan raya sepanjang 70 kilometer, bendungan dan irigasi di Menes.
Hasil kerja paksa mereka kini menjadi fasilitas publik. Ironisnya, masyarakat menyebutnya “Bendungan PKI”—karena dibangun oleh para tahanan politik. “Bendungan itu masih dipakai sampai sekarang,” katanya lirih. “Tapi orang tidak tahu siapa yang membuatnya.”
Kembali ke Tahanan dan Menuju Nusa Kambangan
Enam tahun lamanya Bisri menjalani kerja paksa di bawah bayang senjata. Tahun 1974, mereka diberitahu akan dibebaskan, namun kenyataannya dibawa ke Kodam III Siliwangi, Bandung, dan ditahan di sel bawah tanah bersama para tentara yang dihukum karena mencuri.
Di tempat lembab itu, cahaya matahari jarang masuk. Mereka tidur di lantai semen, saling curiga untuk bertahan. Tapi suatu hari, seorang perwira memandang Bisri dan berkata, “Hati-hati dengan orang ini. Dia orang kulon (barat).” Menurut Bisri, kalimat itu merupakan pengakuan bahwa Bisri adalah orang kuat, keras dan tidak mudah dikalahkan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggunya.
Beberapa bulan kemudian, sekitar delapan puluh tahanan dipindahkan malam-malam menaiki bus menuju Cilacap. Dari sana mereka diseberangkan dengan kapal pengangkut sapi—penuh kotoran dan bau busuk. Ombak besar mengguncang kapal seminggu penuh, hingga akhirnya di kejauhan tampak sebuah pulau: Pulau Buru.
Pulau Buru: Hidup, Bertahan, dan Membangun
Mereka turun dari kapal di muara Sungai Wayapu. Di sepanjang jalan menuju barak, tampak gantungan ubi dan singkong rebus di pohon—bekal kecil yang ditinggalkan tahanan sebelumnya. “Rupanya itu tanda solidaritas dari para tahanan yang sudah mendahului kami,” kata Bisri. “Tanda bahwa di tempat buangan pun masih ada manusia yang peduli.”
Bisri ditempatkan di Barak Dua, bersama kawan-kawan dari Jawa Barat, dan diangkat menjadi kepala barak. Hari-hari pertama diisi apel dan latihan keras. “Pelajaran pertama saya: kalau disuruh siap, harus siap betul. Kalau tidak, ditendang,” katanya getir.
Lima bulan kemudian, para tahanan diperintahkan untuk hidup mandiri. Mereka menebang hutan, mengeringkan rawa, membuka ladang dengan peralatan primitif. “Kami menanam jagung, pisang, singkong, apa saja yang bisa tumbuh,” ujarnya. Ketika panen datang, hasil mereka sering dirampas tentara. Tapi Bisri memilih strategi lain—menanam di pinggir jalan agar mudah dijaga dan bahkan mengizinkan tentara mengambil hasilnya jika lapar. Sejak itu, kekerasan terhadap kelompoknya berkurang.
Dalam setahun, baraknya menjadi yang paling mandiri di antara sembilan barak. Mereka tak lagi bergantung pada jatah tentara. “Kami hidup dari tanah sendiri,” ujarnya bangga.
Di Pulau Buru, sekat agama hilang. “Kami semua satu,” katanya. “Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan—semua saudara.” Ia sering ikut misa, makan roti bersama teman-teman Katolik. “Kami semua manusia yang sama nasibnya.”
Harapan dan Pendidikan di Tanah Buangan
Tahun-tahun berlalu. Suatu ketika datang kabar bahwa ada utusan dari luar negeri—mungkin wartawan, mungkin PBB—yang ingin memeriksa kehidupan para tahanan. Mereka tidak boleh bicara dengan rombongan itu, tapi beberapa tahanan berhasil bertemu diam-diam.
“Salah satu dari mereka orang Barat,” kata Bisri. “Dia bilang, mereka menekan pemerintah agar kami dibebaskan.” Kabar itu menyalakan kembali semangat hidup di hati para tahanan.
Sejak itu, suasana di Pulau Buru perlahan berubah. Mereka mulai mengadakan pendidikan: kursus pertanian, kesehatan, teknik, bahasa asing, bahkan akupunktur. Para siswa pertanian dan calon mahasiswa IPB datang belajar praktik di sana. “Kami yang dulu tahanan, jadi guru lapangan,” katanya.
Bisri sendiri belajar fotografi dan pengobatan tradisional. “Saya mau punya keahlian kalau nanti keluar,” ujarnya. Dari tempat buangan, mereka membangun sekolah kehidupan.
Pembebasan dan Pulang ke Tanah Jawa
Tahun 1977 datang pengumuman: akan ada pembebasan. Para tahanan bersorak, berpelukan, sebagian menangis. Gelombang pertama berangkat tahun 1977, gelombang kedua tahun 1978. Bisri termasuk yang terakhir bebas, tahun 1979—setelah empat belas tahun di pembuangan.
Ia kembali ke Bandung untuk pendataan akhir, lalu ke Banten. “Saya pulang dengan kulit hitam terbakar matahari, tapi masih hidup,” katanya. Namun kebebasan itu setengah. Di KTP-nya tercetak huruf merah besar: E.T. (Eks Tapol)—tanda pengkhianat.
Dengan cap itu, tidak ada pekerjaan yang mau menerima. Setiap minggu ia wajib lapor ke Koramil. “Bebas tapi tetap diawasi,” ujarnya getir. Tapi Bisri tidak menyerah. Ia memohon izin berdagang. Setelah berdebat dengan sersan Koramil, ia diizinkan berjualan kelapa muda. Dari situ ia mulai menata hidup lagi.
Dari Gerobak ke Istana Cendana
Setelah lepas pengawasan, Bisri pergi ke Jakarta. Ia menumpang di kawasan Senen, tidur di lantai beralas tikar. “Saya bingung, mau usaha apa,” katanya. Hingga suatu hari ia melihat pedagang gerobak susu kacang kedele. Ia meminjam gerobak kosong dan mulai berjualan. Setiap hari ia setor sembilan ratus rupiah, berkeliling dari Jelambar ke Jembatan Dua, di bawah panas matahari.
“Saya sudah biasa dipukul,” ujarnya sambil tertawa. “Sekarang cuma diusir Satpol, apa susahnya?”
Setahun kemudian, usahanya maju. Ia lalu diterima bekerja sebagai sekuriti di perusahaan besar milik Grup Cendana. Karena kejujurannya, ia menemukan kecurangan besar: sopir truk mencuri bahan bakar. Laporannya membuatnya dipromosikan dan diangkat tetap. Suatu hari ia ditugaskan menjaga rombongan perusahaan yang menghadiri acara di Istana Cendana, kediaman Presiden Soeharto.
“Bayangkan,” katanya pelan, “orang yang dulu dibuang ke Pulau Buru, sekarang berdiri di tangga Cendana.”
Ia tidak menaruh dendam, hanya diam lama. “Hidup ini lucu,” ujarnya akhirnya.
Membangun Keluarga dan Martabat
Sambil bekerja, Bisri kembali berdagang: menjual emping melinjo dari Banten ke Jakarta. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyekolahkan sebelas anak dan cucu—enam di antaranya sarjana, dua masih kuliah. “Puji Tuhan,” katanya, “sekarang keluarga saya hidup baik. Semua dari kerja keras.”
Ia tak pernah menulis buku, tidak berpidato, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin kisahnya diketahui—bukan untuk menuntut, melainkan untuk mengingatkan.
“Kami bukan pemberontak. Kami manusia yang pernah dihapus, tapi tetap berusaha hidup. Saya tidak mau menyesal. Kalau saya menyesal, saya kalah. Tapi kalau saya bisa tertawa lagi, itu artinya saya menang.”katanya menutup kisah.