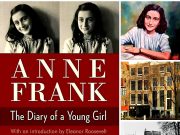Jakarta — Stagnasi dan kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai tidak cukup diatasi dengan reformasi prosedural semata. Diperlukan sebuah kontrak sosial baru yang mengikat ulang relasi antara warga negara, negara, dan kekuatan pasar secara moral dan politis. Gagasan ini mengemuka dalam kuliah terbuka bertajuk “Kontrak Sosial Baru: Mengatasi Stagnasi Demokrasi” yang disampaikan oleh dosen filsafat STF Driyarkara, Dr. Antonius Widyarsono, di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (12/12).
Kuliah ini merupakan seri kesembilan sekaligus penutup rangkaian Kuliah Terbuka Klik Rakyat, sebuah forum diskusi publik yang sejak September 2025 secara konsisten membahas isu politik, demokrasi, kewargaan, ekonomi, ekologi, hingga kebudayaan. Program ini digelar melalui kerja sama Perpustakaan Jakarta, PDS HB Jassin, Ikatan Keluarga Alumni STF Driyarkara, serta jaringan Suara Ibu Indonesia.
Dalam paparannya, Romo Widi, begitu dia biasa disapa menelusuri kembali akar teori kontrak sosial klasik yang lahir pada abad ke-17 dan 18 sebagai respons atas kecemasan terhadap tirani monarki absolut. Ia merujuk pada pemikiran tiga filsuf utama—Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau—yang sama-sama menekankan bahwa legitimasi negara bersumber dari persetujuan warga, bukan dari klaim ilahi atau kekuasaan turun-temurun.
“Teori kontrak sosial pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan mendasar: mengapa kita harus taat pada negara?” ujar Widi. Menurutnya, teori ini menjadi fondasi etika politik modern karena menempatkan persetujuan dan tindakan sukarela warga sebagai dasar legitimasi kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, gagasan kontrak sosial justru direalisasikan dalam bentuk demokrasi perwakilan elektoral yang kini mengalami distorsi serius. Demokrasi yang seharusnya membatasi kekuasaan negara dan menjamin kedaulatan rakyat, dinilai berubah menjadi sarana lahirnya tirani baru.
“Wakil yang dipilih melalui pemilu sering kali tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partai, elite, dan oligarki,” kata Widi. Ia menambahkan bahwa tren global menunjukkan ancaman demokrasi justru datang dari aktor-aktor yang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian mengadopsi strategi otoriter.
Dalam konteks Indonesia, Widi menilai bangsa ini setidaknya telah melewati dua momen kontrak sosial. Kontrak sosial pertama terjadi pada Proklamasi 17 Agustus 1945, yang melahirkan Republik Indonesia dengan janji kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Kontrak sosial kedua muncul pada Reformasi 1998, ketika otoritarianisme Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan masyarakat sipil dan kaum muda.
Namun, menurutnya, kontrak sosial pasca-Reformasi itu kini mengalami erosi serius. Oligarki ekonomi menguat, partai politik terjebak dalam transaksi kekuasaan, oposisi melemah, dan parlemen semakin kehilangan fungsi representatifnya. “Situasi satu dekade terakhir merupakan bentuk terburuk dari degradasi demokrasi pasca-Reformasi,” ujarnya.
Karena itu, Widi menekankan urgensi membangun kontrak sosial baru yang tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan substantif. Kontrak sosial ini, katanya, harus menata ulang hubungan antara warga, negara, dan pasar demi tercapainya keadilan sosial yang nyata.
Ia juga menyoroti kembali peran historis kaum muda dalam Revolusi 1945 sebagai pengingat bahwa perubahan politik fundamental selalu lahir dari keberanian warga untuk berbicara dan bertindak. “Kontrak sosial baru hanya mungkin lahir jika warga negara kembali menjadi subjek aktif demokrasi,” tegas Widi.
Kuliah terbuka ini ditutup dengan diskusi bersama peserta yang menegaskan kegelisahan kolektif atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini, sekaligus membuka ruang imajinasi tentang masa depan politik yang lebih adil dan partisipatif.