Jakarta — Dalam sebuah diskusi bertajuk “Bandung+70: Membedah Ulang Warisan Geopolitik, Meneropong Masa Depan Dunia Selatan,” Forum Praksis menghadirkan dua pembicara utama—pengkaji geopolitik Hendrajit dan sejarawan Romo Baskara T. Wardaya, SJ. Diskusi yang berlangsung di Kolese Kanisius, Jakarta pada Jumat, 28 November 2025 itu menjadi ruang refleksi komprehensif atas relevansi Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 dalam merespons perubahan tatanan dunia yang kembali bergejolak.
Di satu sisi, Hendrajit menekankan kedalaman strategi geopolitik KAA; di sisi lain, Romo Baskara mengajak peserta masuk ke lanskap moral dan historis dari kolonialisme serta dampaknya hingga hari ini. Keduanya menghadirkan sudut pandang yang berbeda namun saling mengisi, membuat pembacaan baru atas Bandung 1955 terasa sangat mendesak.
Indonesia di Garis Depan: Dari Colombo 1954 ke Bandung 1955
Hendrajit membuka paparannya dengan menunjukkan bagaimana Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif—yang dicanangkan Bung Hatta pada 1948—menjadi dasar strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran penting di panggung global. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia bersikap mandiri di tengah tekanan dua blok besar Perang Dingin: Amerika Serikat dan sekutu Baratnya di satu sisi, serta Uni Soviet–RRT di sisi lainnya.
Semangat kemandirian inilah yang dibawa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ketika menerima undangan Konferensi Colombo pada 1954. Meski pertemuan Colombo pada awalnya hanya forum informal untuk membahas ketegangan Indochina, Ali melihatnya sebagai pintu masuk untuk menghidupkan gagasan solidaritas Asia–Afrika.
Lewat arsip-arsip diplomatik, terungkap bahwa jauh sebelum berangkat ke Colombo, pemerintah Indonesia telah menyiapkan konsep konferensi Asia–Afrika yang lebih luas. Ali bahkan menyatakan secara terbuka, “Saya mengusulkan kemungkinan mengadakan suatu konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia-Afrika… dengan pegangan teguh politik luar negeri bebas yang aktif.”
Namun sambutan para pemimpin negara lain saat itu dingin. Nehru, misalnya, khawatir bahwa perbedaan pandangan antarnegara terlalu besar untuk mencapai kesepakatan. Ia meramalkan gagasan itu sulit diwujudkan. Tetapi sejarah berkata lain. Berkat diplomasi tekun Indonesia, Colombo melahirkan political opening yang menentukan: Indonesia diberi mandat menyiapkan KAA. Dari pertemuan persiapan Bogor pada Desember 1954, lima negara sponsoring menyepakati Bandung sebagai tuan rumah.
KAA pun akhirnya diselenggarakan pada 18–24 April 1955, menghadirkan 29 negara Asia–Afrika dan menjadi pusat perhatian dunia.
Peta Geopolitik Bung Karno yang Terlupakan
Salah satu bagian paling kuat dari paparan Hendrajit adalah penjelasannya tentang konsep “garis hidup imperialisme” dalam pidato pembukaan Bung Karno di KAA. Menurutnya, banyak yang mengingat retorika Bung Karno tetapi melupakan substansi geopolitiknya. Bung Karno memetakan jalur-jalur maritim dari Selat Gibraltar, Terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia hingga Pasifik sebagai urat nadi kolonialisme global. Jalur itu menjadi alur pergerakan kekuasaan, perdagangan, dan dominasi selama berabad-abad.
Hendrajit menyebut pemetaan ini sebagai “kode sejarah” yang dibongkar Bung Karno. “Para pendiri bangsa menemukan sejarah agar bisa membaca masa depan,”kata Hendrajit.
Ia menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat soft power maritim—dari Inggris di Cina hingga Belanda di Nusantara. Inilah yang membuat KAA menjadi perlawanan moral sekaligus strategis terhadap imperialisme.
Menurut Hendrajit, KAA bukan sekadar forum solidaritas. Ia menciptakan kekuatan ketiga (the third force) di luar Blok Barat–Timur. Meski Nehru awalnya skeptis, KAA justru berhasil merumuskan kesepakatan politik bersama melalui Dasasila Bandung, yang kemudian menjadi fondasi lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB) di Beograd pada 1961.
Hendrajit menyebut, keberhasilan KAA dimungkinkan karena enam faktor perekat: persamaan pengalaman kolonial,
aspirasi kemerdekaan, kecemasan terhadap perang dingin, dinamika politik Asia pasca-Korea, belum adanya forum global non-barat, dan kesamaan masalah pembangunan. Dari sinilah muncul identitas kolektif Global South.
Mengungkap Luka Kolonialisme dan Dampak Perang Dingin
Sejarawan Indonesia Romo Baskara T. Wardaya SJ dalam sesi lanjutan menyampaikan pendekatan sejarah kritis, ia menggali dimensi moral dan kemanusiaan di balik KAA. Dia mengingatkan bahwa kolonialisme bukan hanya perebutan wilayah, tetapi penghancuran sistematis terhadap: identitas budaya, kedaulatan politik, struktur ekonomi lokal, dan rasa percaya diri bangsa-bangsa terjajah.
KAA, menurut Baskara, adalah momen ketika suara bangsa-bangsa yang terluka itu akhirnya terdengar. “Di Bandung, korban kolonialisme berbicara tanpa mediator. Itu revolusioner,”ujarnya.
Baskara lalu membongkar fakta-fakta arsip. Katanya, Amerika Serikat sebenarnya mengawasi konferensi dengan ketat karena takut muncul blok baru anti-Barat. Sementara Uni Soviet dan Cina memandang KAA sebagai peluang memperluas pengaruh ideologis. Operasi intelijen kedua blok berlangsung bahkan sebelum KAA dibuka.
KAA, menurut Baskara menjadi ruang di mana negara-negara baru merdeka mencoba berbicara, sementara dua negara adidaya berusaha mengatur dari balik panggung. Karena itu, kata Baskara, KAA pada dasarnya adalah panggung “pembalikan narasi kekuasaan.” Barat tidak lagi menjadi pusat percakapan; Asia–Afrika mengambil alih definisi tentang kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan global.
KAA menginspirasi gerakan pembebasan di Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara, hingga Asia Barat. Ia menyatukan moralitas baru yang kuat: bangsa-bangsa yang pernah dikuasai kolonialisme kini menolak ditentukan masa depannya oleh negara besar manapun.
Meski KAA berhasil menyatukan aspirasi, Romo Baskara mengingatkan bahwa visi Bandung belum selesai. Banyak negara peserta terjebak kembali dalam: kudeta militer, perang saudara, intervensi asing, utang luar negeri, dan ketergantungan ekonomi baru.
Menurutnya, negara-negara Global South gagal menyelesaikan agenda KAA karena terjebak dalam permainan geopolitik negara besar. “KAA adalah mimpi besar. Kita meninggalkannya setengah jalan,”ujar Baskara.
Relevansi untuk Dunia Kini
Baik Hendrajit maupun Romo Baskara sepakat bahwa dunia saat ini kembali memasuki situasi mirip 1950-an: rivalitas dua adidaya membuat negara berkembang menjadi medan perebutan pengaruh. Negara-negara Global South berada di persimpangan: apakah tetap menjadi objek geopolitik, atau kembali menjadi subjek seperti yang dimulai di Bandung.
Hendrajit mendorong pentingnya menghidupkan kembali GNB dengan konteks modern, sedangkan Romo Baskara mengingatkan perlunya imajinasi politik untuk memetakan masa depan. “Pertanyaannya bukan apakah Global South bisa bersatu, tetapi apakah kita berani menentukan masa depan kita sendiri.”ujar Baskara.
Diskusi ditutup dengan sebuah pernyataan penting dari kedua pembicara yang menyebutkan bahwa Indonesia pernah, dan masih bisa, memainkan peran moral dan strategis bagi dunia Selatan. 70 tahun setelah Bandung, tantangannya tetap sama: ketimpangan global, persaingan adidaya, ketergantungan struktural, dan kebutuhan membangun solidaritas.
Namun peluangnya juga tetap besar. Sejarah menunjukkan bahwa ketika negara-negara bekas jajahan berani bersuara bersama, dunia mendengarnya.












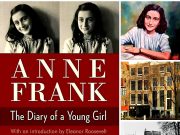

















Asem ik. Mas Abdi ki laporan n tulisannya cen enak dibaca. Juga seputar sejarah ya detail tgl n tempat tersaji tepat.
Bravo mas Abdi. Teruslah berkarya lewat tulisan. 👍👍