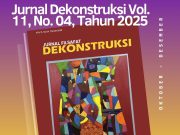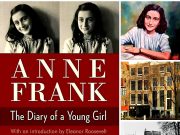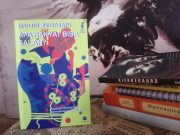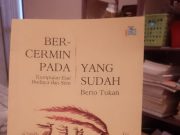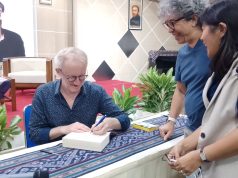Jakarta — Peneliti INKRISPENA, Ruth Indiah Rahayu, menegaskan bahwa peristiwa 1965 harus dibaca bukan semata sebagai tragedi politik, tetapi sebagai titik tolak pembentukan sistem kerja paksa dan akumulasi primitif kapitalisme Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ruth dalam diskusi reflektif Forum PRAKSIS bertema Memaknai Resiliensi Sebagai Bahasa Kemanusiaan Pasca-1965, yang menyoroti pengalaman para tahanan politik di berbagai kamp kerja seperti Pulau Buru, Plantungan, dan Nanga-Nanga. Dalam forum tersebut hadir pula Bisri (93 tahun), salah satu eks tapol dari Banten yang berbagi kisahnya tentang kerja paksa yang dialamiya selama kurang lebih 14 tahun di Pulau Buru.
“Tragedi 1965 bukan sekadar pembunuhan politik, melainkan juga awal proses perampasan tanah dan tenaga manusia untuk diindustrialisasikan. Di situ terjadi akumulasi kapital secara brutal dalam masa yang bukan lagi kolonial,” ujar Ruth di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) ini menjelaskan bahwa akumulasi primitif—istilah dalam teori Marxian—menggambarkan proses pengambilalihan tanah dan tenaga kerja petani mandiri agar dapat dieksploitasi dalam sistem produksi kapitalis. Setelah 1965, Indonesia memasuki era industrialisasi di bawah kekuasaan militer, dan ribuan tahanan politik dipaksa bekerja dalam proyek-proyek pembangunan tanpa upah dan tanpa hak.
Kerja Paksa di Balik “Rehabilitasi”
Menurut Ruth, berbagai riset menunjukkan adanya pola sistematis kerja paksa terhadap tahanan politik pasca-1965. Dalam proses itu, negara tidak hanya memenjarakan manusia, tetapi juga memproduksi tenaga kerja murah untuk kepentingan pembangunan.
Ia memetakan sedikitnya tiga pola besar kerja paksa yang muncul di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, perampasan tanah. Di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, eks-tapol dikerahkan untuk mengelola kembali perkebunan peninggalan Belanda yang telah diambil alih oleh militer. Tanah yang sebelumnya dikuasai rakyat atau perusahaan asing dijadikan lahan baru bagi negara dan korporasi militer.
Kedua, pembukaan hutan. Di Pulau Buru, ribuan tahanan politik dipaksa membuka hutan, menanam padi, dan membangun permukiman. Aktivitas mereka bukan sekadar “rehabilitasi,” melainkan bagian dari kebijakan kolonisasi dalam rangka memperluas produksi pangan nasional.
Dan ketiga, pembangunan fasilitas militer dan umum. Dijelaskan oleh Ruth, di berbagai daerah, termasuk di Plantungan dan Nanga-Nanga, para tahanan perempuan dan laki-laki disuruh bekerja membersihkan lahan bekas rumah sakit, membangun jalan, bendungan, dan fasilitas umum yang kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah dan militer.
“Semua pola ini menandai keterlibatan negara dalam eksploitasi tenaga manusia tanpa persetujuan bebas,” ujar Ruth. Ia menegaskan, praktik-praktik tersebut memenuhi unsur forced labour sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930: kerja di bawah ancaman hukuman, tanpa kebebasan memilih, dan tanpa upah layak.
Dari Tapol ke Buruh Prekariat
Bagi Ruth, penderitaan para penyintas tidak berhenti ketika mereka keluar dari kamp. Setelah bebas, mereka tetap kehilangan akses ekonomi dan sosial, hidup sebagai buruh serabutan, pedagang kecil, atau pekerja informal.vKondisi ini menandakan transformasi dari kerja paksa fisik ke kerja paksa ekonomi—bentuk baru dari ketidakbebasan dalam sistem kapitalisme.
Kisah Bisri, mantan tahanan politik dari Banten, menjadi contoh nyata yang ia sebut sebagai “pengetahuan primer dari bawah.” Selama belasan tahun, Bisri menjadi tenaga kerja paksa dalam proyek pembangunan pelabuhan, bendungan, dan jalan raya. Setelah bebas, ia bekerja sebagai pedagang kaki lima di Jakarta sebelum akhirnya diterima sebagai satpam di sebuah perusahaan besar.
“Pengalaman seperti Pak Bisri ini penting karena ia bukan sekadar korban, tapi juga saksi sejarah tentang bagaimana tubuh manusia dijadikan instrumen produksi kekuasaan,” kata Ruth.
Advokasi Baru: Perspektif Kerja Paksa
Ruth menilai, isu kerja paksa bisa menjadi pintu baru untuk mengadvokasi penyintas Tragedi 1965 secara hukum internasional. Ia menekankan bahwa Konvensi ILO telah digunakan untuk menuntut kejahatan serupa dalam kasus kamp konsentrasi Nazi, dan bisa pula diterapkan di konteks Indonesia.
“Pendekatan ini memungkinkan kita keluar dari kebuntuan advokasi HAM yang selama ini hanya berputar di ranah politik dan moral. Dengan kerja paksa sebagai dasar, kita punya landasan hukum internasional yang kuat,” ujarnya.
Merawat Ingatan, Melawan Penghapusan
Ruth juga mengusulkan dua agenda penting: pertama, memorialisasi kerja paksa; kedua, penyelamatan memori sebagai politik pengetahuan. Situs-situs seperti Bendungan Menes di Banten—yang dibangun oleh tahanan politik dan dikenal warga sebagai “bendungan PKI”—menurutnya layak ditetapkan sebagai situs memorial kerja paksa nasional.
Selain itu, ia mendorong dokumentasi dan penulisan kesaksian para penyintas agar menjadi bagian dari politik pengetahuan yang menantang narasi resmi negara.
“Kita harus melawan penghapusan sejarah melalui produksi dan distribusi pengetahuan alternatif. Ingatan para penyintas adalah fondasi politik budaya kita,” tegas Ruth.
Bagi Ruth Indiah Rahayu, pengalaman seperti Bisri menegaskan bahwa tubuh yang pernah dihukum negara kini menjadi sumber pengetahuan dan etika kemanusiaan. Kisah mereka tidak hanya membuka sisi gelap sejarah, tetapi juga mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh lagi berdiri di atas penderitaan manusia.
“Mereka yang dulu dituduh pengkhianat justru mengajarkan pada kita apa arti ketekunan dan kemanusiaan,” pungkasnya.