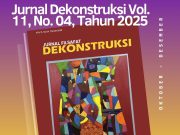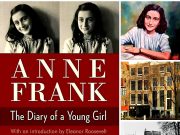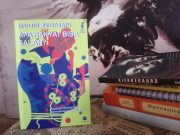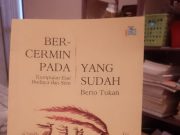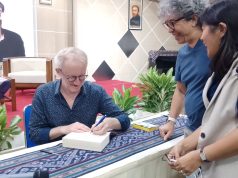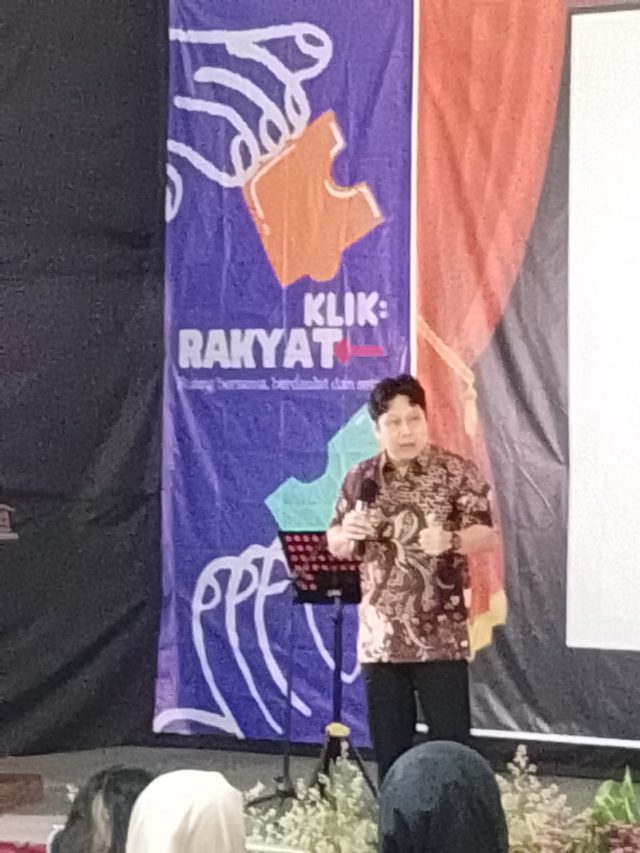
JAKARTA — Guru Besar Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta Profesor Robertus Robet menilai Indonesia sedang mengalami krisis republikanisme. Demokrasi memang berjalan, tetapi republik—sebagai semangat, etika, dan ruang hidup bersama warga—pelan-pelan lenyap dari kesadaran publik.
Demikian disampaikan Robet dalam Kuliah Terbuka program Klik:Rakyat bertajuk “Menguji Republikanisme di Indonesia” yang digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Acara yang diinisiasi oleh Suara Ibu Indonesia (SII) bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) dan Himpunan Mahasiswa Driyarkara (HMD) ini dihadiri puluhan mahasiswa, akademisi, dan aktivis sosial.
Dalam paparannya, Robet menyatakan bahwa republik yang diperjuangkan para pendiri bangsa kini hidup di bawah bayang-bayang oligarki, klientelisme, dan politik kartel. Menurutnya, ada tiga lapisan krisis besar yang membentuk wajah politik Indonesia masa kini. Di tingkat bawah, kehidupan politik rakyat dikendalikan oleh relasi klientelistik—politik yang ditukar dengan uang, sembako, atau janji-janji material. Di tingkat menengah, partai-partai politik meninggalkan basis sosialnya (konstituen) dan membentuk kartel kekuasaan semata untuk mempertahankan sumber daya ekonomi dan posisi politik. Di tingkat paling atas, oligarki menggunakan politik untuk akumulasi kekayaan mereka sendiri.
“Politik kita sudah diubah oleh logika ekonomi,” ujar Robet. “Institusi-institusi politik, yang semestinya menjadi arena perjuangan nilai dan gagasan, kini menjadi mesin pengumpulan kekayaan. Namanya masih partai politik, tetapi isinya bukan lagi politik. Yang terjadi adalah ekonomisasi politik.” Ia menegaskan, ketika seluruh perangkat politik telah berubah fungsi menjadi mekanisme ekonomi, maka tidak ada lagi tempat bagi perjuangan isu-isu mendasar seperti kebebasan, keadilan, kesejahteraan umum dan hak asasi. Politik kehilangan makna, dan bersama itu republik pun kehilangan ruhnya. “Tidak ada tempat bagi korban, bagi isu-isu fundamental, tentang common good. Apa itu keadilan, kebebasan,”kata Robet.
Robet menyebut kondisi ini sebagai paradoks pascareformasi. “Kita menemukan demokrasi, tetapi kehilangan republik,” katanya. Menurutnya, reformasi 1998 berhasil membuka ruang kebebasan dan menggulingkan otoritarianisme, tetapi gagal membangun lembaga dan budaya republikan yang mampu menjaga kebebasan itu. Demokrasi yang hidup tanpa republik akhirnya melahirkan politik transaksional dan warga negara yang kehilangan rasa tanggung jawab terhadap sesamanya. Politik kehilangan martabatnya sebagai tindakan bersama untuk kebaikan umum, berubah menjadi arena transaksi dan persaingan kepentingan pribadi.
Ketika republik runtuh, hubungan antarwarga juga ikut rusak. Nilai kesetaraan perlahan pupus. “Lihat saja di dunia hukum: keluarga kelas menengah kini dengan mudah memidanakan guru hanya karena tersinggung, menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Kalau yang menengah saja bisa begitu, bagaimana dengan orang kaya atau pejabat berkuasa? Mereka merasa dapat membeli hukum demi menuntaskan dendam pribadi,”ujar Robet.
Budaya politik kita jadi busuk, kata Robet menegaskan. Politik yang seharusnya menjadi ruang martabat berubah menjadi ruang komersial dan kekuasaan.
Kekuatan Politik Baru
Di tengah situasi politik yang penuh persoalan saat ini, menurut Robet, kita bisa berharap pada munculnya kekuatan politik alternatif—terutama yang bersumber dari kaum muda. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di satu sisi, kaum muda dijadikan tumpuan harapan politik baru; di sisi lain, mereka dihantam oleh berbagai stigma yang melemahkan semangat politik mereka. Sementara pada level menengah dan atas, praktik politik masih sangat bergantung pada elit lama. Inilah kontradiksi mendasar dalam politik Indonesia hari ini.
Kehancuran yang kita hadapi bukan hanya bersifat struktural, melainkan juga kultural—yakni kehancuran dari semangat res publica itu sendiri: lenyapnya ruang politik yang sungguh-sungguh publik. Namun, masih ada titik terang. Tahun 2019, muncul gerakan mahasiswa dengan tagar #ReformasiDikorupsi, yang menolak berbagai rancangan undang-undang bermasalah seperti RUU KUHP. Meskipun secara praktis gerakan itu gagal menghentikan legislasi, secara kultural ia berhasil menyehatkan kembali sebagian budaya politik Indonesia yang sebelumnya rusak akibat polarisasi pasca Pilpres 2014.
Setelah 2014, ruang publik politik Indonesia seolah hanya diisi oleh dua kutub: pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Tidak ada lagi politik kewargaan. Gerakan mahasiswa 2019 memunculkan alternatif baru—mengingatkan kita bahwa di luar dua kutub kekuasaan itu, masih ada ruang bagi warga untuk bersuara. Kekalahan gerakan itu pun bermakna, sebab ia menghidupkan kembali kesadaran politik warga.
Dari sinilah kita dapat melihat relevansi republikanisme. Tradisi ini menekankan pentingnya budaya kewargaan (civic culture) dan politik partisipatif. Dalam pandangan civic republicanism, kebebasan sejati hanya mungkin muncul lewat keterlibatan warga dalam kehidupan politik. Partisipasi bukan sekadar hak, melainkan cara manusia menjadi manusia.
Namun, seperti dijelaskan Philip Pettit dalam versi neo-republicanism, fokus republikanisme modern tidak lagi berhenti pada partisipasi individual, tetapi meluas pada pembangunan institusi politik dan hukum yang mencegah kekuasaan arbitrer (arbitrary power). Dalam dunia politik kontemporer yang sarat dominasi ekonomi dan oligarki, yang diperlukan bukan sekadar orang baik, melainkan sistem yang baik—karena kekuasaan pribadi selalu berpotensi menyimpang jika tidak dikontrol oleh mekanisme institusional.
Indonesia membutuhkan pemikiran politik yang progresif dan berakar kuat dalam tradisi sendiri. Kita hidup dalam masyarakat hibrid—campuran antara yang tradisional dan modern—sehingga kita perlu gagasan politik yang memiliki akar historis, kekuatan moral, dan kerangka institusional yang jelas. Dari ketiga kriteria itu, republikanisme menawarkan jalan yang paling menjanjikan.
“Pertama, republikanisme bersifat progresif karena ingin mengembalikan politik sebagai tindakan bermartabat, bukan sebagai perpanjangan logika ekonomi atau alat kekuasaan keluarga. Kedua, republikanisme menekankan partisipasi warga dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang publik. Ketiga, ide ini tidak asing bagi tradisi politik Indonesia,”ujar Robet.
Jika menengok ke sidang BPUPK tahun 1945, terlihat bahwa perdebatan tentang bentuk negara—antara Soekarno, Hatta, Yamin, dan Supomo—pada dasarnya merupakan perdebatan tentang republikanisme. Saat itu, Indonesia memutuskan untuk menjadi republik, bukan kerajaan. Namun, sayangnya, elaborasi filosofis atas pilihan itu berhenti di sana. Setelah kemerdekaan, hampir tidak ada upaya serius untuk mendidik warga tentang apa arti republikanisme itu sendiri.
Sukarno, Hatta, dan Tan Malaka sempat menyentuh gagasan republik dalam berbagai tulisan mereka, namun tidak sampai membentuk kerangka konseptual yang kokoh. Dalam buku Herbert Feith, kita bahkan bisa menemukan siaran pers dari Masjumi Sumatera Timur yang menegaskan semangat republik dengan kalimat: “Sungguh suatu keganjilan di dalam sebuah negara yang bernama republik masih ada unsur-unsur feodal di dalamnya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa republikanisme pernah hidup sebagai semangat politik anti-feodal.
Namun, setelah itu, republikanisme menghilang dari wacana politik Indonesia. Ia tinggal sebagai nama—tanpa isi ideologis. Sejak masa Orde Baru, kita tak lagi memiliki perangkat konseptual untuk menilai politik secara republik. Setelah Reformasi pun, yang muncul adalah teori-teori baru tentang demokrasi dan civil society, tetapi bukan republikanisme. Akibatnya, sistem politik kita kehilangan orientasi moral dan ideologis.
Karena itu, republikanisme perlu dihidupkan kembali—bukan sebagai nostalgia masa lalu, tetapi sebagai landasan ide untuk mereformasi sistem politik Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir dari non-domination, bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan partisipasi warga, dan bahwa politik harus dikembalikan menjadi tindakan bermartabat yang memperjuangkan kebaikan bersama.
Riwayat Republikanisme
Dalam uraian filosofisnya, Robet membawa hadirin menelusuri akar republikanisme sejak Yunani kuno hingga pemikiran modern. Gagasan awal republikanisme berakar pada filsafat politik Aristoteles, yang membedakan antara polis dan oikos—dua ranah kehidupan yang memiliki logika dan tujuan berbeda. Dalam padanan Latin, keduanya dikenal sebagai res publica dan res privata.
Apa itu oikos? Oikos adalah wilayah kehidupan yang digerakkan oleh dorongan untuk bertahan hidup—the mode of survival. Dalam dunia oikos, manusia berjuang untuk mempertahankan keberadaannya. Ada tiga bentuk utama oikos: pertama, rumah tangga yang berfokus pada reproduksi biologis; kedua, ekonomi (oikonomia) yang mengatur kelangsungan hidup melalui produksi dan distribusi; dan ketiga, militer yang menjaga keamanan dari ancaman luar. Ketiganya berada dalam ranah kehidupan yang ditentukan oleh kebutuhan untuk bertahan.
Sebaliknya, polis adalah ranah kehidupan yang didorong oleh logika deliberatif—ruang tempat manusia berdialog, berdebat, dan mencari kebaikan bersama. Dari sinilah lahir gagasan tentang manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang sejatinya hidup dan menjadi manusia melalui keterlibatannya dalam kehidupan politik.
Ketika pemikiran Yunani ini kemudian berpindah ke Italia, terjadi pergeseran dalam pemaknaan. Dalam tradisi republikanisme yang berkembang di sana, zoon politikon berubah menjadi homo civilis. Pergeseran ini dimungkinkan karena prinsip pemisahan antara polis dan oikos dinormativitaskan melalui karya-karya pemikir seperti Gayus Cicero. Dengan demikian, muncul distingsi yang jelas antara res publica (urusan publik) dan res privata (urusan pribadi).
Prinsip ini menjadi dasar bagi republik: kehidupan politik tidak boleh bercampur dengan urusan rumah tangga atau kepentingan keluarga. Dunia politik harus memiliki batas yang tegas. Kaum republikan menolak keras jika lembaga-lembaga negara digunakan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga, sebab dalam republik sejati, kekuasaan tidak boleh diwariskan seperti harta. Politik harus dipisahkan dari logika survival—dari ekonomi, militer, maupun keluarga—agar tidak berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi.
Namun, pemisahan yang begitu ketat antara ranah privat dan publik ini kemudian dikritik oleh para feminis, khususnya pada dekade 1960-an. Mereka mempertanyakan: jika dunia politik dipisahkan sepenuhnya dari ruang privat, di mana tempat bagi perempuan yang selama ini ditempatkan di wilayah domestik? Kritik tajam ini antara lain datang dari Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan yang dalam karya klasiknya The Human Condition meninjau kembali batas-batas antara privat dan publik.
Dari sinilah muncul civic humanism—suatu bentuk humanisme politis yang berkembang kuat di Italia, terutama di Firenze pada abad ke-15. Civic humanism berpijak pada gagasan bahwa manusia sejati adalah manusia yang berpolitik; bahwa partisipasi politik merupakan ekspresi tertinggi dari kemanusiaan. Negara, dalam pandangan ini, adalah perwujudan maksimum dari politik warga negara.
Pemikiran ini menemukan bentuk rasionalnya dalam karya Niccolò Machiavelli, tokoh penting dalam tradisi politik modern. Machiavelli memperkenalkan dua konsep utama: virtù dan fortuna. Virtù mewakili hal-hal yang pasti, yang dapat dikendalikan manusia melalui akal dan kehendak; sedangkan fortuna adalah wilayah ketidakpastian dan kebetulan. Berpolitik, bagi Machiavelli, berarti berlayar di antara keduanya—mengambil keputusan dengan akal dalam menghadapi nasib yang tak menentu.
Dengan cara pandang ini, Machiavelli menegaskan bahwa politik adalah urusan rasional, bukan lagi ditentukan oleh kekuatan adikodrati. Ia menempatkan politik di ranah sekuler, menjauhkan dari mistifikasi dan mitologi kekuasaan. Inilah tonggak penting dalam sejarah civic humanism: lahirnya pemahaman bahwa berpolitik adalah tindakan rasional dan etis yang mendefinisikan kemanusiaan itu sendiri.
Selanjutnya Robet mengajak peserta untuk memasuki gagasan filsuf dan teoritikus politik asal Irlandia, Philip Noel Pettit AC (lahir 1945). Pettit dikenal sebagai pembela utama aliran republikanisme sipil (civic republicanism) dalam filsafat politik. Bukunya yang berjudul Republicanism: A Theory of Freedom and Government menjadi dasar teoretis bagi berbagai reformasi politik di Spanyol pada masa pemerintahan José Luis Rodríguez Zapatero.
Philip Pettit memulai gagasan republikanismenya dengan menolak dua teori besar tentang kebebasan: kebebasan negatif dan kebebasan positif.
Kebebasan negatif, seperti dikemukakan oleh Isaiah Berlin, didefinisikan sebagai bebas dari campur tangan (freedom from interference). Sementara itu, kebebasan positif—yang dikembangkan oleh Rousseau dan Hegel—disebut sebagai freedom as self-mastery, yaitu kebebasan untuk menguasai diri sendiri, menaklukkan hasrat, dan tunduk pada hukum yang dibuat sendiri.
Namun, bagi Philip Pettit, kedua konsep ini tidak memadai. Kebebasan negatif terlalu sempit, sedangkan kebebasan positif terlalu tebal. Untuk menjelaskan posisi Pettit, Robet menggunakan contoh tentang seorang majikan dan asisten rumah tangganya, analogi yang membantu menjelaskan inti dari kebebasan sebagai non-domination (kebebasan tanpa dominasi).
“Bayangkan seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja pada keluarga kelas menengah yang baik. Ia tidak mengalami campur tangan: boleh menonton Netflix, berjalan-jalan di akhir pekan, bahkan menggunakan telepon majikannya. Namun, meskipun tidak ditindas, hidupnya tetap berada di bawah kekuasaan arbitrer—karena nasib dan kebebasannya masih bergantung pada kehendak majikannya. Dalam kondisi seperti itu, kata Pettit, orang itu tidak sungguh-sungguh bebas,”ujar Robet.
Maka, kebebasan sejati bukan sekadar bebas dari gangguan (non-interference), melainkan bebas dari dominasi (non-domination). Pettit, kata Robet menulis, “to be free is to live without being subject to the arbitrary will of another”. Artinya, menjadi bebas berarti hidup tanpa tunduk pada kehendak sewenang-wenang orang lain. Yang dimaksud dengan arbitrary di sini bukan soal baik atau buruknya seseorang, melainkan soal status sosial dan ketergantungan struktural.
Dengan demikian, yang penting bukan hanya apakah seseorang diganggu atau tidak, melainkan apakah ia hidup dalam posisi setara, bebas dari kekuasaan yang tidak terkontrol.
Beda Fokus
Demi memperjelas uraian tentang konsep republikanisme, Robet lantas menjelaskan perbedaan utama antara civic humanism klasik dan neo-republikanisme Pettit. Semua terletak pada fokusnya, katanya.
Dalam tradisi civic humanism—dari Machiavelli hingga Hannah Arendt—kebebasan berarti partisipasi aktif warga dalam republik. Kebebasan diperoleh melalui tindakan dan keterlibatan politik: berpartisipasi, berdeliberasi, dan mengambil bagian dalam kehidupan publik.
Sebaliknya, dalam neo-republikanisme, fokusnya bergeser dari tindakan ke institusi politik dan hukum. Bagi Pettit, kebebasan warga hanya dapat dijamin melalui sistem dan mekanisme yang mencegah munculnya kekuasaan arbitrer. Karena itu, politik tidak lagi cukup dijalankan dengan mencari “orang baik,” melainkan dengan membangun sistem yang baik. Orang baik tanpa sistem yang adil tetap berpotensi menjadi sumber dominasi, sebab tidak ada jaminan bahwa ia akan selalu baik.
Relevansi bagi Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pemikiran Pettit menjadi sangat relevan. Saat ini, menurut Robet, banyak “orang baik” yang justru tergelincir dalam populisme—fenomena yang kerap melemahkan institusi politik. Populisme, kata Pettit, adalah penyakit dalam demokrasi karena menggunakan kekuatan ekstra-politik untuk merongrong tatanan institusional.
Neo-republikanisme menekankan bahwa untuk mencegah kekuasaan arbitrer, yang perlu diperkuat adalah institusi politik dan hukum—agar warga tidak lagi hidup dalam situasi dominasi. Dalam kerangka ini, etika politik yang penting adalah akuntabilitas dan deliberasi, bukan hanya moral pribadi.
Pettit juga menekankan pentingnya democratic contestability, yaitu kemampuan warga untuk mengoreksi kekuasaan melalui mekanisme hukum dan politik. Ini berarti kebebasan diuji melalui ruang kritik: apakah hukum melindungi orang yang mengkritik, dan apakah masyarakat memiliki konsensus bahwa kritik adalah bagian dari kewargaan.
Dalam semangat reformasi republikan, tegas Robet, politik perlu didefinisikan kembali sebagai arena dignitas—ruang tempat manusia menegakkan martabatnya melalui tindakan dan sistem yang adil. Mengutip semangat civic humanism, manusia sejati adalah manusia yang berpolitik, bukan untuk menguasai, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang hidup di bawah kekuasaan sewenang-wenang.
Contohnya terlihat dalam perjuangan yang belum selesai untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Penolakan terhadap RUU ini—dengan alasan “tidak sesuai budaya Indonesia” atau “terlalu kapitalistik”—menunjukkan bahwa kekuasaan politik masih beroperasi melalui jalur-jalur informal, bukan mekanisme formal yang adil. Ini, menurut W. Warren Shot, menandakan keroposnya demokrasi akibat informalisasi kekuasaan.
Menjaga Republik
“Karena itu, menjaga republik berarti menjaga agar warga tidak hidup dalam dominasi, baik oleh individu, keluarga, maupun kelompok oligarki. Politik yang sehat menuntut sistem hukum yang menjamin ruang kritik dan partisipasi warga, sebab seperti dikatakan Hannah Arendt, politik adalah tindakan kolektif, bukan individual,”ujar Robet.
Politik sejati selalu bersifat publik dan dilakukan bersama. Dalam jembatan antara civic humanism dan neo-republikanisme, Arendt menjadi tokoh kunci: ia menegaskan bahwa politik bukan sekadar urusan negara, tetapi cara manusia menghidupi kebebasan bersama.
Maka, sebagaimana disimpulkan Robet dalam kuliahnya, problem dan solusi politik Indonesia sama-sama ada di masa lalu. Dengan meninjau ulang akar republikanisme—dari Aristoteles hingga Pettit—kita dapat menemukan kembali fondasi ideologis untuk membangun politik yang bermartabat dan bebas dari dominasi.
“Problem-problem dalam demokrasi dan kepolitikan kita maupun solusinya ada di dalam masa lalu kita. Maka, reformasi republikan itu mesti dimulai dengan memikirkan sejarah politik kita. Problemnya ada di situ, tetapi masa depan politik kita ada di situ juga,”ujar Robet.
Serial Kuliah Terbuka Klik:Rakyat
Kuliah ini merupakan bagian dari program KLIK: Rakyat, ruang reflektif yang digagas Suara Ibu Indonesia untuk mendengarkan dan meneguhkan suara warga dalam menata kehidupan publik. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif antara berbagai unsur, meliputi individu, ikatan alumni, program studi universitas dan sekolah tinggi, serta media penyiaran. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pengembangan diskursus kebangsaan dan kebudayaan Indonesia setelah 80 tahun kemerdekaan, sekaligus menyongsong peringatan 100 tahun Republik Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan menguatkan literasi partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi bagi kokohnya solidaritas dan pemahaman kebangsaan Indonesia. Melalui rangkaian diskusi, kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan dan strategi bagi peningkatan kualitas demokrasi, perwujudan nilai-nilai kerakyatan, serta penguatan semangat ke-republik-an Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dan dinamika perubahan geopolitik dunia.
Seri ini dibuka pada 29 September 2025 di kampus STF Driyarkara oleh Prof. Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, dengan tema “Sejarah 1965–1966 dan Politik Kiri di Indonesia.” Dalam kuliah ini, Prof. Magnis menelusuri akar kekerasan politik dan dinamika ideologi kiri di Indonesia, serta pentingnya memahami sejarah secara jujur untuk membangun kehidupan politik yang berkeadaban.
Berlanjut pada 6 Oktober 2025 di Perpustakaan Nasional RI, Dr. Augustinus Setyo Wibowo, dosen STF Driyarkara sekaligus Pemimpin Redaksi Basis, membawakan topik “Demokrasi, Agonisme, dan Oposisi Permanen.” Ia mengulas bagaimana demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang bagi perbedaan dan oposisi yang berkelanjutan sebagai elemen kritis dari kehidupan politik.
Pada 13 Oktober 2025, giliran Dr. Irine Hiraswari Gayatri, Direktur Eksekutif Komite Pelaksana Program Management of Social Transformation UNESCO di Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berbicara di Guyonan Cafe. Dalam paparannya berjudul “Pasang-Surut Kerakyatan dalam Relasi Kuasa,” Irine menguraikan bagaimana rakyat kerap menjadi objek dari perubahan politik, dan bagaimana kekuasaan dapat diarahkan untuk mengembalikan ruang partisipasi rakyat yang sejati.
Sementara itu, Prof. Robertus Robet, Guru Besar Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta, tampil pada 21 Oktober 2025 di STF Driyarkara dengan kuliah bertajuk “Menguji Republikanisme Indonesia.” Robet menyoroti krisis politik Indonesia yang menurutnya ditandai oleh “ekonomisasi politik” dan hilangnya semangat republikan, di mana politik telah kehilangan martabatnya sebagai ruang deliberasi publik.
Tema lingkungan dan keadilan hidup menjadi sorotan Dr. Ruth Indiah Rahayu, pengajar Studi Gender Universitas Indonesia, pada 27 Oktober 2025 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM). Dalam kuliah berjudul Hirarki Hutang : Pencederaan Politik Kehidupan – Ariel Shalleh dan Metabolisme Nilai Ruth menggambarkan bagaimana sistem ekonomi global menciptakan ketimpangan struktural antara utang ekologis, sosial, dan finansial, yang menindas kelompok dan alam di pinggiran.
Memasuki November, pada 3 November 2025, Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D, dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, akan menguraikan topik “Menjadi Warga di Zaman Krisis Keadilan: Mempertimbangkan Agensi Nonparlementer.” Ia akan membahas bagaimana warga negara dapat mengambil peran aktif di luar struktur formal politik untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Kuliah berikutnya pada 10 November 2025 akan mengangkat tema “Politik Konsekuensi dan Tanggung Jawab Lintas Generasi.” Meski pembicara belum diumumkan, topik ini diharapkan membahas etika politik dalam menghadapi krisis global dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Pada 17 November 2025, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), akan tampil di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dengan kuliah berjudul “Mengkritik ‘Sihir’ Pertumbuhan.” Huda akan mengajak publik meninjau ulang paradigma ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.
Rangkaian kuliah akan ditutup pada 24 November 2025 di Menara Kompas, dengan Dr. Karlina Supelli, Ketua Program Doktor Ilmu Filsafat STF Driyarkara, melalui kuliah berjudul “Pertumbuhan, Kebudayaan, dan Masa Depan Demokrasi: Siasat bagi Kontrak Sosial Baru.” Supelli akan menyoroti kebutuhan untuk membangun kembali kontrak sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keberlanjutan.
Dengan tema-tema yang menyentuh akar persoalan politik, ekonomi, dan kebudayaan, Seri Kuliah Filsafat Publik Klik:Rakyat menjadi ruang penting untuk memperdalam refleksi kritis atas arah demokrasi dan masa depan kehidupan bernegara di Indonesia.