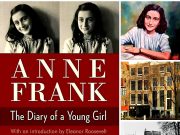Jakarta – Bagaimana nasib “suara rakyat” di tengah pusaran kekuasaan global dan oligarki politik yang semakin menguat? Pertanyaan inilah yang mengemuka dalam Kuliah Publik Program KLIK: RAKYAT kerja sama Suara Ibu Indonesia (SII), Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD), dan Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang digelar di Guyonan Café, Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Peneliti Senior pada Klaster Politik Luar Negeri, Pusat Riset Politik BRIN Doktor Irine Hiraswari Gayatri menjelaskan tema besar berjudul “Pasang-Surut Kerakyatan: Rakyat dalam Arus Perubahan Sosial dan Demokrasi Global.” Dalam paparannya, Irine mengurai dinamika peran rakyat dari masa ke masa — dari euforia Reformasi 1998 hingga kemunduran demokrasi yang kini mulai terasa.
“Kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar selesai diperjuangkan. Ia mengalami pasang dan surut, tergantung sejauh mana rakyat mampu mempertahankan kontrol terhadap kekuasaan,” ujar Irine di hadapan para peserta yang memenuhi ruang diskusi.
“Kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar selesai diperjuangkan. Ia mengalami pasang dan surut, tergantung sejauh mana rakyat mampu mempertahankan kontrol terhadap kekuasaan,”
Demokrasi dan Pasang-Surut Kedaulatan Rakyat
Sejarah Indonesia, menurut Irene, memperlihatkan gelombang besar partisipasi rakyat yang kerap diikuti masa stagnasi. Reformasi 1998 menjadi titik pasang tertinggi ketika rakyat berhasil menumbangkan rezim otoriter. Namun, dua dekade kemudian, gelombang itu surut saat oligarki politik dan ekonomi kembali menguasai sistem pemerintahan.
Ia menyoroti bagaimana UU Cipta Kerja dan UU Minerba menjadi contoh konkret “demokrasi yang dibajak kepentingan elite.” “Proses legislasi berjalan, tetapi substansi kebijakan sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil,” kata Irine, seraya menambahkan bahwa checks and balances melemah karena koalisi partai yang terlalu besar.
Sebelumnya, Irine mengajak peserta kuliah menelusuri akar filsafat “kerakyatan” dari berbagai tradisi. Di Eropa (Barat), Irine mengutip Rousseau tentang “kehendak umum”, Marx tentang perjuangan kelas, hingga John Dewey yang memaknai demokrasi sebagai “a way of life.”
Sementara dari Timur, ia menyoroti nilai-nilai Konfusianisme, Islam, dan tradisi Jawa yang menekankan kepemimpinan berbasis kebajikan, musyawarah, dan gotong royong. “Pancasila sebenarnya adalah sintesis luhur antara rasionalitas Barat, etika Timur, dan spiritualitas Nusantara. Ia menempatkan rakyat bukan sebagai obyek, tapi mitra dalam kebijakan publik,” jelas Irine.
Belajar dari Filipina, Myanmar, dan Thailand
Irine kemudian memperluas cakrawala dengan meninjau kasus internasional. Di Filipina, semangat People Power 1986 berhasil menggulingkan diktator Marcos, tetapi tanpa reformasi struktural, oligarki kembali berkuasa melalui populisme Duterte dan kini Marcos Jr.
Di Myanmar, rakyat berkali-kali bangkit namun dihancurkan militer, menunjukkan bahwa tanpa kontrol sipil, demokrasi tak bisa bertahan. Sedangkan di Thailand, kemenangan partai reformis Move Forward pada 2023 digagalkan senat pro-militer—menegaskan bahwa mandat rakyat masih bisa dijegal oleh elit konservatif.
“Dari ketiga kasus ini kita belajar, kekuatan rakyat bisa menumbangkan rezim, tapi tanpa transformasi struktural, kekuasaan lama akan selalu kembali dalam bentuk baru,” tegas Irine.
Dalam konteks Indonesia hari ini, Irine melihat munculnya kembali gerakan rakyat sebagai respons terhadap konsolidasi kekuasaan elite. Aksi protes bertajuk “Indonesia Gelap” awal 2025 disebutnya sebagai simbol baru perlawanan sipil terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak transparan.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan kondisi statis, melainkan proses yang terus diperjuangkan. “Eternal vigilance is the price of liberty — kewaspadaan rakyat adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga demokrasi tetap hidup,” ujarnya menutup kuliah publik tersebut.